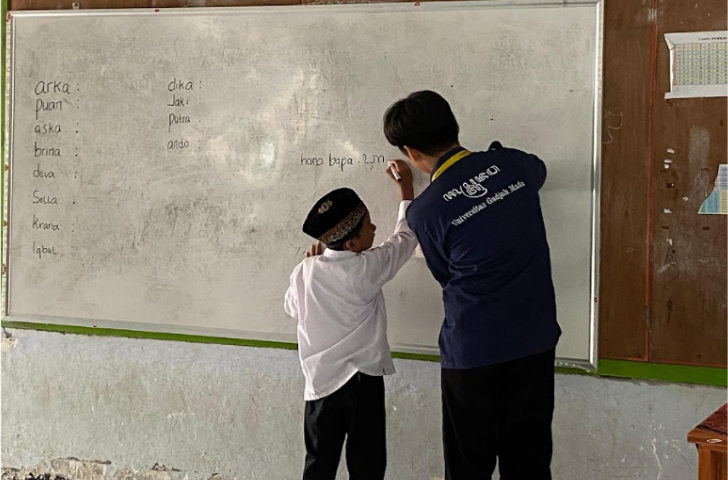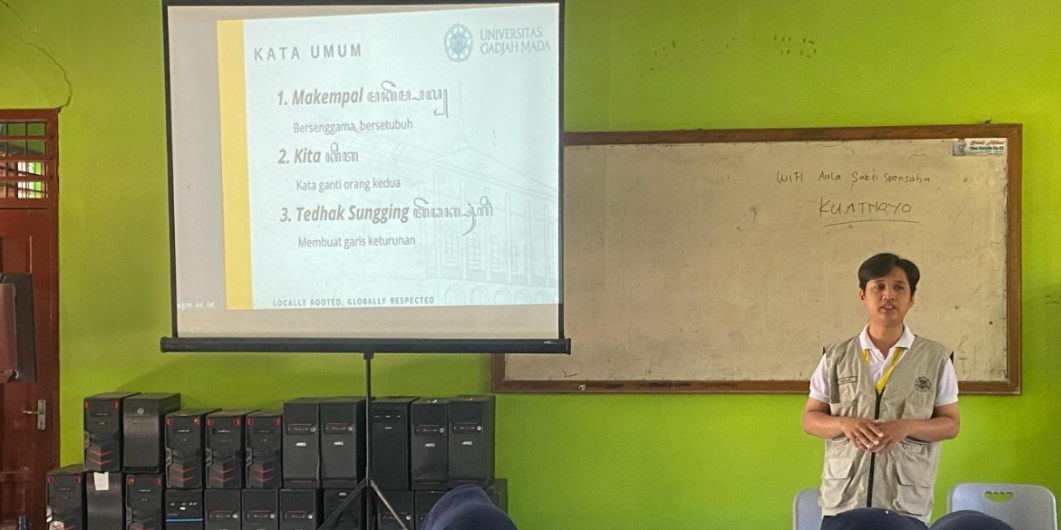Yogyakarta, 28/8/2025 – Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) kembali menghadirkan ruang diskusi ilmiah melalui workshop bertajuk “Archives of Ethnographic Encounters”. Acara yang digelar di Ruang Multimedia Gedung Margono, berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.00 WIB dan menghadirkan Marco Del Gallo, kandidat doktor Antropologi di London School of Economics.
Dalam kesempatan ini, Marco berbagi pengalamannya bekerja dengan arsip fotografi pribadi milik mendiang Haswinar Arifin, seorang mahasiswa antropologi sekaligus fotografer yang mendokumentasikan kehidupan di Jakarta Utara sejak dekade 1970-an hingga awal 2000-an. Melalui arsip tersebut, Marco mengajak peserta merenungkan kembali bagaimana arsip bukan hanya sekadar kumpulan dokumen, melainkan jejak hidup yang menyimpan cerita, emosi, dan dinamika sosial.
Diskusi berkembang pada pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar definisi arsip. Apakah setiap orang, dengan kebiasaan menyimpan foto, catatan, atau rekaman, sesungguhnya sedang menghasilkan dokumen sejarah masa depan? Jika demikian, bagaimana peneliti harus memperlakukan arsip—baik miliknya maupun milik orang lain—sebagai bahan penelitian? Refleksi ini membuka ruang untuk melihat arsip bukan semata dokumen resmi, melainkan juga foto, rekaman suara, video, hingga tulisan kreatif yang merekam pengalaman sehari-hari.
Di sisi lain, Marco menekankan adanya tanggung jawab etis dalam bekerja dengan arsip yang dikumpulkan oleh orang lain. Arsip pribadi yang kemudian dibawa ke ruang akademik menyimpan dilema tersendiri: bagaimana menjaga keintiman dari materi tersebut ketika dipublikasikan? Apa batas antara tanggung jawab peneliti, hak kepemilikan, dan kepentingan masyarakat yang menjadi bagian dari arsip itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut peneliti untuk peka terhadap etika, kepedulian, dan bentuk kolaborasi yang adil.
Pengalaman Marco sendiri berangkat dari penelitian doktoral yang didasarkan pada 26 bulan kerja lapangan di komunitas nelayan Jakarta Utara. Penelitiannya berkontribusi pada perbincangan akademik seputar urbanisme, kapitalisme, transformasi lingkungan, politik kolektif, hingga dinamika kerja. Kehadirannya di FIB UGM memperlihatkan bagaimana pengalaman etnografis yang terjalin di lapangan dapat dipertemukan dengan refleksi teoretis yang lebih luas melalui arsip.
Workshop ini akhirnya tidak hanya menjadi forum pertukaran pengetahuan, tetapi juga pengingat bahwa arsip adalah ruang hidup yang merekam masa lalu sekaligus membuka kemungkinan baru bagi penelitian di masa depan. Melalui arsip, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana kehidupan sehari-hari bisa menjadi sejarah, dan bagaimana merawat arsip berarti juga merawat ingatan kolektif.
[Humas FIB UGM, Candra Solihin]