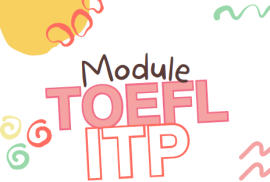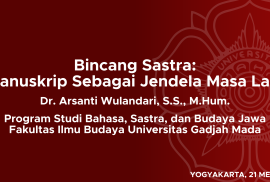SDGs 4: Quality Education | SDGs 8: Decent Work and Economic Growth | SDGs 11: Sustainable Cities and Communities | SDGs 16: Peace, Justice, and Strong Institutions | SDGs 17: Partnerships for the Goals
Minggu, 12 Mei 2024, bertempat di The Ratan, Kampung Mataraman, Bantul, diselenggarakan diskusi buku ke-10 dalam gelaran acara Jogja Art and Book Festival. Sekitar pukul 15.10 WIB diskusi novel Tangan Kotor di Balik Layar dengan narasumber Puthut EA selaku penulis dan Saeful Anwar selaku pembahas dibuka oleh Abdul Rahman yang menjadi moderator. Di hadapan sekitar 50-an peserta, diskusi dimulai dengan pemaparan hasil pembacaan Saeful Anwar yang secara garis besar mengaitkan antara tradisi penulisan kritik atas pemerintahan yang sedang berjalan dalam novel-novel Indonesia dan muatan kritik dalam karya Puthut EA. Di samping itu, dalam bahasan pertama itu, narasumber juga mengungkapkan kesan adanya distraksi akibat nama-nama tokoh dalam novel berasal dari tokoh-tokoh nyata di sekitar penulis.
Puthut EA selaku penulis mengakui hal tersebut dan mengungkapkan bahwa ia memiliki kelemahan dalam mengingat nama-nama sehingga menggunakan nama-nama yang dikenalnya dalam keseharian sebagai solusi atas masalah tersebut. Puthut juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kritik pada kekuasaaan yang sedang berjalan bukanlah fokus utama novel tersebut. Ia menyatakan bahwa novelnya lebih ditujukan untuk memperkarakan kondisi masyarakat sekarang yang mudah sekali mengkultuskan seseorang. Hal ini juga direspons oleh narasumber yang menyitir pendapat Pierre Bourdie bahwa ada kecenderungan masyarakat sekarang menganggap seseorang yang memiliki keistimewaan sebagai auctor (nabi), bukan sebagai lector (guru/pengajar). Jika seorang nabi dipercayai dan diyakini karena personalnya, seorang guru/pengajar diikuti bukan karena personalnya, melainkan karena ajaran yang dibawanya. Nah, masyarakat sekarang cenderung kehilangan kekritisan, sehingga tidak melihat apa ajarannya, tapi siapa sosoknya.
Dalam sesi tanya jawab muncul banyak pertanyaan, antara lain, apa motivasi penulisan novel (untuk penulis) dan sejauh mana motivasi itu berhasil dituangkan dalam novel (untuk narasumber), dapatkah seseorang mengkritik novel tanpa tahu teori sastra, bagaimana jika novel yang dibaca ternyata memiliki ciri sebagai novelet yang cenderung ringkas dan sekali duduk dalam membaca, mengapa kritik terhadap penguasa jarang muncul dalam karya, dan adakah kemungkinan penulis diperkaran secara hukum karena kritik dalam karyanya?
Semua pertanyaan tersebut bergantian dijawab oleh penulis dan narasumber dengan memberikan uraian masalah dan contoh-contoh kasusnya. Diskusi diakhiri dengan kesimpulan bahwa novel Tangan Kotor di Balik Layar memang tidak menjadikan kritik pada pemerintah sebagai pusat cerita, tetapi merupakan daya tarik utama dari novel ini karena isu yang masih aktual