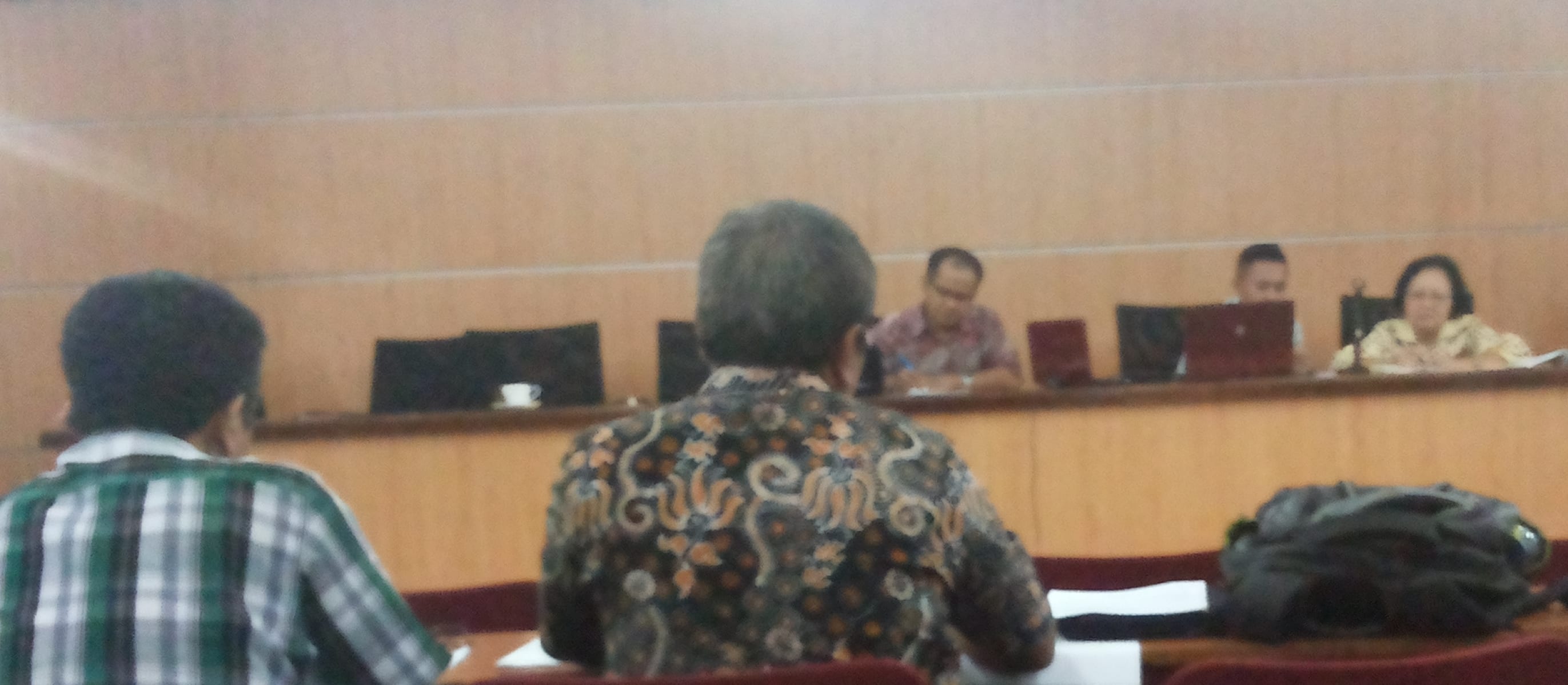Sadar atau tidak, kebanyakan dari hasil penelitian kita mengekor pada konsep-konsep yang dihadirkan oleh peneliti Asing, sehingga kita tidak pernah merdeka dari “penjajahan” ilmu pengetahuan Barat. Padahal, Nusantara memiliki tradisi dan sastra lisan yang penuh dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan dan peradaban yang kaya dalam bentuk pewarisan sastra dan tradisi lisan.
“Dahsyatnya konsep pengetahuan lokal tidak kalah dengan pengetahuan luas yang selalu kita impor. Konsep “Tsunami” misalnya, yang menggambarkan gelombang tinggi yang terjadi di Pantai Barat Sumatra sampai Aceh. Pengetahuan local masyarakat Simeleu (Aceh) telah lama mengenal konsep pengetahuan tentang gelombang besar tersebut dengan “mong” atau “smong”. Gambaran konsep pengetahuan local lain tentang “Living Green” yang ada pada masyarakat Riau. Dan dalam konteks ini, masuknya perkebunan kelapa sawit telah menghilangkan living green yang mengakar pada masyarakat Riau. Karena konsep pengetahuan local itu tidak pernah dihadirkan, maka sumber pengetahuan local nusantara semakin tidak terdengar gaungnya.
Hal itu disampaikan Prof. Dr. Bambang Purwanto dalam Pengantar Seminar Program Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora bertema “Tradisi Lisan, Sastra Lisan dan Sejarah Lisan dalam Perspektif Kajian Kritis” di Ruang Margono, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Rabu 4 Juli 2014.
Prof. Bambang menambahkan bahwa kebiasaan sebagian peneliti Indonesia tidak memanfaatkan dan menghadirkan konsep-konsep local dalam kajiannya sehingga konsep-konsep local yang demikian baik itu tidak mampu berdialog dengan konsep-konsep yang lebih dulu dihadirkan oleh peneliti lainnya.
Dalam konteks ini, peneliti yang ada pada level paling tinggi seharusnya menghadirkan konsep-konsep lokal Nusantara yang kaya itu ke dalam penelitian mereka sehingga dialog dengan konsep yang sudah ada bisa berdialog dengan baik dalam ranah ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan Sastra Lisan, Tradisi Lisan dan Sejarah Lisan.
Diakhir pengantarnya, Prof. Bambang mengajak para peneliti (mahasiswa S3 yang sedang menyusung Disertasi) agar memanfaatkan potensi pengetahuan dan peradaban local yang kaya itu dalam penelitian mereka. “Belum tentu yang tertulis dalam teks itu lebih hebat daripada yang lisan. Pengabaian tradisi lisan sebagai sumber sejarah (sebagai sumber pengetahuan) selama ini telah mengabaikan banyak peradaban yang ada di Nusantara”, ulasnya.
Contributor:
La Ode Rabani, FIB-UGM